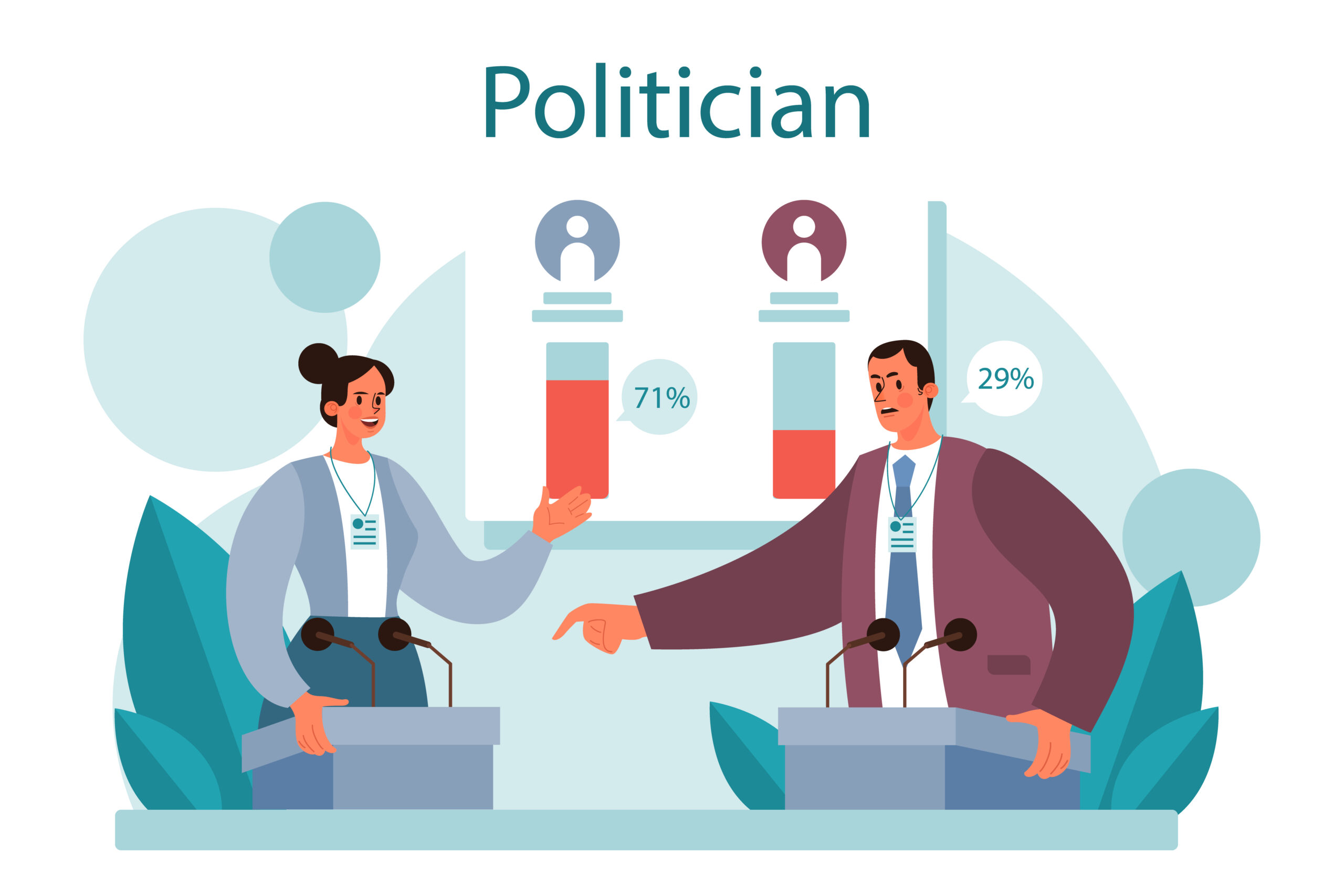Gender Dan Kekuasaan. Dari kursi parlemen hingga istana presiden, keterwakilan perempuan nyaris selalu berada di angka minoritas. Perempuan sering kali diposisikan sebagai pendukung, bukan pemegang kendali utama. Ini bukan semata masalah pilihan, melainkan hasil dari struktur sosial yang telah membatasi ruang gerak mereka selama berabad-abad.
Ketimpangan gender dalam politik bermula dari nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam kebudayaan banyak bangsa. Sejak awal, perempuan dianggap tidak cukup rasional, terlalu emosional, dan tidak layak memegang kekuasaan publik. Norma ini diperkuat oleh sistem pendidikan dan hukum yang dulu tidak memberikan akses setara pada perempuan. Bahkan hingga awal abad ke-20, banyak negara masih menolak hak pilih bagi perempuan.
Namun, sejarah juga mencatat perempuan-perempuan tangguh yang menembus batas itu. Tokoh seperti Indira Gandhi di India, Margaret Thatcher di Inggris, dan Angela Merkel di Jerman adalah contoh nyata bahwa perempuan bisa memimpin negara dengan stabilitas dan ketegasan. Di Asia Tenggara, tokoh seperti Corazon Aquino dan Megawati Soekarnoputri juga menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi simbol transisi politik yang kuat.
Meski demikian, keberadaan tokoh-tokoh ini belum cukup untuk menghapus ketimpangan secara struktural. Mereka sering dianggap pengecualian, bukan norma. Bahkan ketika seorang perempuan berhasil menduduki posisi puncak, ia masih harus menghadapi keraguan publik, sorotan terhadap penampilan fisik, hingga pelecehan berbasis gender yang jarang dialami pemimpin laki-laki.
Ketimpangan gender dalam politik bukan hanya soal siapa yang duduk di tampuk kekuasaan, tapi juga siapa yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan di berbagai level. Keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga pengawas, partai politik, dan jajaran eksekutif masih jauh dari proporsional. Masalah ini bersifat sistemik dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkat satu-dua perempuan sebagai simbol.
Gender Dan Kekuasaan dalam politik bukan sebagai perebutan kekuasaan antarjenis kelamin, tapi sebagai upaya memperluas ruang partisipasi publik bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.
Hambatan Sistemik Dan Budaya: Gender Dan Kekuasaan Politik Yang Belum Inklusif
Hambatan Sistemik Dan Budaya: Gender Dan Kekuasaan Politik Yang Belum Inklusif. Jika ditanya apakah perempuan ingin memimpin, banyak yang menjawab “ya.” Namun, realitanya, jalan menuju kekuasaan bagi perempuan jauh lebih terjal di bandingkan laki-laki. Hambatan ini bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam sistem politik itu sendiri.
Partai politik, misalnya, sering kali lebih percaya pada figur laki-laki untuk maju dalam kontestasi karena dianggap lebih “kuat” atau “punya jaringan.” Perempuan kerap dihadapkan pada standar ganda: jika tegas, disebut galak; jika lembut, dianggap lemah. Bahkan dalam perebutan posisi internal partai, perempuan lebih sulit mendapat dukungan, baik karena bias budaya maupun karena kurangnya akses ke sumber daya politik.
Sementara itu, sistem kampanye yang membutuhkan dana besar juga menjadi tantangan tersendiri. Perempuan, terutama yang bukan berasal dari keluarga elite politik, sering tidak memiliki sumber dana atau jaringan donor yang sama dengan kandidat laki-laki. Kondisi ini menciptakan ketimpangan sejak awal.
Selain hambatan struktural, ada juga hambatan kultural yang lebih halus namun tidak kalah kuat: ekspektasi sosial terhadap perempuan. Di banyak masyarakat, perempuan masih dibebani peran domestik yang besar, sehingga sulit untuk mencurahkan waktu dan energi ke dunia politik yang sangat menuntut. Bahkan ketika seorang perempuan maju sebagai calon pemimpin, sering kali yang dipersoalkan adalah status pernikahannya, jumlah anaknya, atau penampilannya—hal-hal yang jarang menjadi sorotan dalam pencalonan laki-laki.
Media massa juga memainkan peran besar dalam memperkuat stereotip ini. Liputan tentang perempuan politikus sering kali fokus pada gaya busana atau kehidupan pribadi, bukan pada visi dan gagasannya. Ini memperkuat citra bahwa perempuan dalam politik adalah “pengecualian” yang perlu dibingkai dalam narasi unik, bukan sebagai bagian normal dari demokrasi.
Kepemimpinan Perempuan: Gaya Baru Dalam Pengambilan Keputusan
Kepemimpinan Perempuan: Gaya Baru Dalam Pengambilan Keputusan. Salah satu hal yang kerap muncul dalam diskusi tentang gender dan kepemimpinan adalah pertanyaan: apakah perempuan memimpin dengan cara yang berbeda? Jawaban singkatnya: tidak selalu, tapi sering kali ya. Perempuan membawa pendekatan dan perspektif yang bisa melengkapi dinamika politik yang selama ini didominasi oleh gaya maskulin.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pemimpin perempuan cenderung lebih kolaboratif, mendengarkan, dan fokus pada dialog. Di masa pandemi COVID-19, misalnya, sejumlah negara yang dipimpin oleh perempuan seperti Selandia Baru (Jacinda Ardern), Jerman (Angela Merkel), dan Finlandia (Sanna Marin) dinilai lebih sigap, komunikatif, dan empatik dalam menangani krisis. Pendekatan kepemimpinan yang berbasis empati dan transparansi ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik.
Selain itu, kehadiran perempuan dalam posisi strategis juga berpengaruh terhadap kebijakan. Penelitian dari World Bank dan UN Women menunjukkan bahwa negara dengan representasi perempuan yang tinggi di parlemen cenderung mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—isu-isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Namun penting dicatat bahwa perempuan tidak otomatis menjadi pemimpin yang “lembut” atau hanya peduli isu sosial. Mereka juga bisa tegas, visioner, dan berani mengambil keputusan sulit, seperti ditunjukkan oleh sosok-sosok seperti Golda Meir, Dilma Rousseff, atau Aung San Suu Kyi. Artinya, kepemimpinan perempuan sangat beragam dan tidak bisa distereotipkan.
Gaya kepemimpinan yang lebih inklusif ini membawa angin segar dalam dunia politik yang kerap terjebak dalam polarisasi dan konfrontasi. Politik tidak lagi harus kaku, penuh rivalitas, atau hanya soal adu otot kekuasaan. Kepemimpinan perempuan membuka ruang untuk politik yang lebih manusiawi dan berorientasi pada dialog.
Namun, untuk menciptakan keseimbangan itu, sistem harus menerima dan menghargai gaya kepemimpinan perempuan, bukan memaksakan mereka untuk meniru model kepemimpinan laki-laki. Inilah tantangan besar dalam menciptakan budaya politik yang benar-benar setara.
Menuju Politik Setara: Quota, Pendidikan, Dan Representasi Nyata
Menuju Politik Setara: Quota, Pendidikan, Dan Representasi Nyata. Menghadirkan lebih banyak perempuan dalam politik bukan hanya soal etika keadilan, tapi juga soal efektivitas pemerintahan. Sistem demokrasi yang sehat adalah sistem yang mencerminkan keberagaman masyarakatnya, termasuk dalam hal gender. Oleh karena itu, upaya mewujudkan politik yang lebih setara harus dilakukan secara sistematis dan terukur.
Salah satu instrumen paling efektif adalah kebijakan kuota. Banyak negara telah memberlakukan kuota gender dalam pencalonan anggota parlemen atau jabatan publik lainnya. Indonesia sendiri memiliki kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, meski implementasinya masih menghadapi tantangan besar.
Kuota bukan bentuk privilese, melainkan langkah afirmatif untuk memperbaiki ketimpangan historis. Tanpa intervensi semacam itu, sistem yang sudah bias akan terus mereproduksi ketimpangan. Namun kuota juga bukan solusi tunggal. Ia harus dibarengi dengan pendidikan politik sejak dini bagi perempuan, pelatihan kepemimpinan, dan dukungan logistik serta jaringan yang memadai.
Representasi perempuan yang bermakna juga harus ditunjukkan dalam substansi kebijakan. Tidak cukup hanya menempatkan perempuan sebagai “pemanis visual” dalam parlemen, tapi memastikan mereka punya suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup isu-isu perempuan, anak, buruh, hingga keberlanjutan lingkungan—yang sering kali luput dari prioritas politik tradisional.
Media dan masyarakat sipil juga memegang peran penting. Masyarakat perlu dididik untuk melihat kepemimpinan perempuan sebagai hal yang normal, bukan anomali. Media pun harus mengubah narasi yang bias dan sensasional terhadap tokoh perempuan, dan mulai menilai mereka berdasarkan kompetensi, bukan gender.
Masa depan politik yang setara membutuhkan kerja kolektif: dari negara, partai politik, masyarakat, hingga perempuan itu sendiri. Jika semua pihak bersedia membuka ruang dan menghapus hambatan, maka jawaban atas pertanyaan “apakah politik siap dipimpin perempuan?” akan berubah dari keraguan menjadi keyakinan sehingga dapat menghapus sistem Gender Dan Kekuasaan.